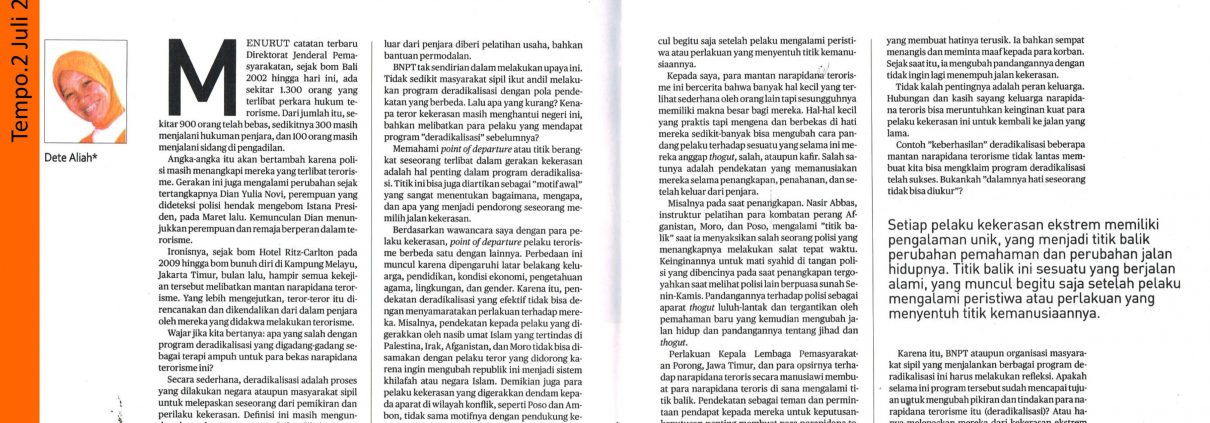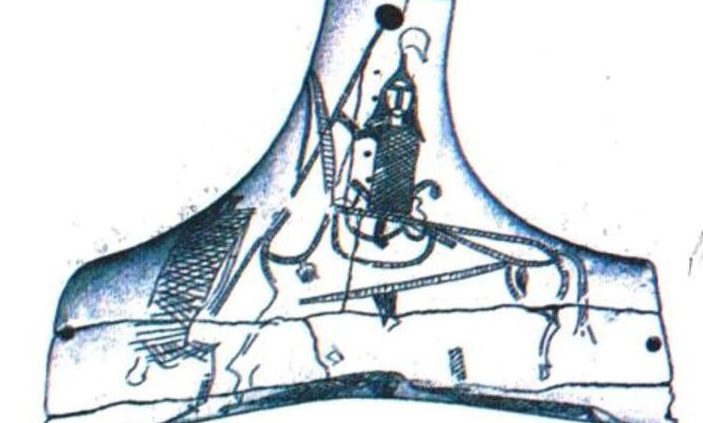Refleksi Program Deradikalisasi

REFLEKSI PROGRAM DERADIKALISASI
Oleh Dete Aliah
MENURUT catatan terbaru Direktorat Jendral Pemasyarakat, sejak bom Bali 2002 hingga hari ini, ada sekitar 1.300 orang yang terlibat perkara hukum terorisme. Dari jumlah itu, sekitar 900 orang telah bebas, sedikitnya 300 masih menjalani hukuman penjara, dan 100 orang masih menjalani sidang di pengadilan.
Angka-angka itu akan bertambah karena polisi masih menangkapi mereka yang terlibat terorisme. Gerakan ini juga mengalami perubahan sejak tertangkapnya Dian Yulia Novi, perempuan yang dideteksi polisi hendak mengebom Istana Presiden, pada Maret lalu. Kemunculan Dian menunjukkan perempuan dan remaja berperan dalam terorisme.
Ironisnya, sejak bom Hotel Ritz-Carlton pada 2009 hingga bom bunuh diri di Kampung Melayu, Jakarta Timur, bulan lalu, hampir semua kekejian tersebut melibatkan mantan narapidana terorisme. Yang lebih mengejutkan, teror-teror itu direncanakan oleh mereka yang didakwa melakukan terorisme.
Wajar jika kita bertanya: apa yang salah dengan program deradikalisasi -yang digadang-gadang sebagai terapi ampuh untuk para bekas narapidana terorisme ini?
Secara sederhana, deradikalisasi adlah proses yang dilakukan negara ataupin masyarakat sipil untuk melepaskan seseorang dari pemikiran dan perilaku kekerasan. Definisi ini masih mengundang banyak pertanyaan. Apakah radikal itu sama dengan perilaku kekerasan? Mungkinkah kita mengubah pemikiran seseorang? Jika mungkin, mengubah pemikiran seseorang? Jika mungkin, apakah alat ukurnya? Atau kita cukup puas dengan hanya mengukur dari perubahan perilaku?
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang diberi mandat oleh pemerintah untuk menangani program deradikalisasi ini, telah melakukan berbagai pendekatan. BNPT mengundang para ustad, ulama bahkan mantan pendiri Jamaah Islamiyah Mesir untuk berduel ideologi dengan para pelaku tindak pidana terorisme ini. Para narapidana terorisme ataupun mereka yang telah keluar dari penjara diberi pelatihan usaha, bahkan bantuan permodalan.
BNPT tak sendirian dalam melakukan upaya ini. Tidak sedikit masyrakat sipil ikut andil melakukan program deradikalisasi dengan pola pendekatan yang berbeda. Lalu apa yang kurang? Kenapa teror kekerasan masih menghantui negeri ini, bahkan melibatkan para pelaku yang mendapat program “deradikalisasi” sebelumnya?
Memahami point of departure atau titik berangkat seseorang terlibat dalam gerakan kekerasan adalah hal penting dalam program deradikalisasi. Titik ini bisa juga diartikan sebagai “motif awal” yang sangat menentukan bagaimana, mengapa, dan apa yang menjadi pendorong seseorang memilih jalan kekerasan.
Berdasarkan wawancara saya dengan para pelaku kekerasan, point of departure pelaku terorisme berbeda satu dengan lainnya. Perbedaan ini muncul karena dipengaruhi latar belakang keluarga, pendidikan, kondisi ekonomi, pengetahuan agam, lingkungan, dan gender. Karena itu, pendekatan deradikalisasi yang efektif tidak bisa dengan menyamaratakan perlakuan terhadap mereka. Misalnya, pendekatan kepada pelaku yang digerakkan oleh nasib umat Islam yang tertindas di Palestina, Irak, Afganistan, dan Moro tidak bisa disamakan dengan pelaku teror yang didorong karena ingin mengubah republik ini menjadi sistem khilafah atau negara Islam. Demikian juga para pelaku kekerasan yang digerakkan dendam kepada aparat di wilayah konflik, seperti Poso dan Ambon tidak sama motifnya dengan pendukung kelompok Negara Islam irak dan Suriah (ISIS) yang hari ini bermunculan karena pengaruh media sosial.
Jadi mendapatkan gambaran yang utuh terhadap point of departure para pelaku teror sangat menentukan langkah atau intervensi apa yang sesungguhnya tepat untuk menderadikalisasi mereka. Lalu kapan dan bagaimana proses deradikalisasi yang efektif?
Setiap pelaku kekerasan ekstrem memiliki pengalaman unik, yang menjadi titik balik perubahan pemahaman dan perubahan jalan hidupnya. Titik balik ini sesuatu yang berjalan alami, yang muncul begitu saja setelah pelaku mengalami peristiwa atau perlakuan yang menyentuh titik kemanusiaannya.
Kepada saya, para mantan narapidana terorisme ini bercerita bahwa banyak hal kecil yang terlihat sederhana oleh orang lain tapi sesungguhnya memiliki makna besar bagi mereka. Hal-hal kecil yang praktis tapi mengena dan berbekas di hati mereka sedikit-banyak bis mengubah cara pandang pelaku terhadap sesuatu yang selama ini mereka anggap thogut, salah, ataupun kafir. Salah satunya adalah pendekatan yang memanusiakan mereka selama penangkapan, penahanan, dan setelah keluar dari penjara.
Misalnya pada saat penangkapan. Nasir Abbas, instruktur pelatihan para kombatan perang Afganistan, Moro dan Poso, mengalami titik balik” saat ia menyaksikan salah seorang polisi yang menangkapnya melakukan salat tepat waktu. Keinginannya untuk mati syahid di tangan polisi yang dibencinya pada saat penangkapan tergoyahkan saat melihat polisi lain berpuasa sunnah Senin-Kamis. Pandangannya terhadap polisi sebagai aparat thogut luluh-lantak dan tergantikan oleh pemahaman baru yang kemudian mengubah jalan hidup dan pandangannya tentang jihad dan thogut.
Pelakuan Kepala Lembangan Permasyarakatan Porong, Jawa Timur, dan para opsirnya terhadap narapidana teroris secara manusiawi membuat para narapidana teroris di sana mengalami titik balik. Pendekatan sebagai teman dan permintaan pendapat kepada mereka untuk keputusan-keputusan penting membuat para narapidana teroris merasa dimanusiakan dan dianggap sebagai mitra, bukan sebagai tahanan. Pendekatan inilah yang mempengaruhi Umar Patek, tokoh penting di balik bom Bali 2002, mengibarkan bendera Merah Putih atas keinginannya sendiri pada hari Kebangkitan Nasional dan menyatakan dirinya menjadi bagian dari Negara Kesatuan RI.
Ali Fauzi, adik kandung Ali Gufron dan Amrozi, pelaku bom Bali 2002, mengaku bahwa titik balik yang membuat dia meninggalkan jalan kekerasan ekstrem adalah saat ini bebas dari penjara dan bertemu dengan para korban bom. Pertemuan inilah yang membuat hatinya terusik. Ia bahkan sempat menangis dan meminta maaf kepada para korban. Sejak saat itu, ia mengubah pandangannya dengan tidak ingin lagi menempuh jalan kekerasan.
Tidak kalah pentingnya adalah peran keluarga. Hubungan dan kasih sayang keluarga narapidana teroris bisa meruntuhkan keinginan kuat para pelaku kekerasan ini untuk kembali ke jalan yang lama.
Contoh “keberhasilan” deradikalisasi beberapa mantan narapidana terorisme tidak lantas membuat kita bisa mengklaim program deradikalisasi telah sukses. Bukankah “dalamnya hati seseorang tidak bisa diukur”?
Setia pelaku kekerasan ekstrem memiliki pengalaman unik, yang menjadi titik balik perubahan pemahaman dan perubahan jalan hidupnya. Titik balik ini sesuatu yang berjalan alami, yang muncul begitu saja setelah pelaku mengalami peristiwa atau perlakuan yang menyentuh titik kemanusiaannya.
Karena itu, BNPT ataupun organisasi masyarakat sipil yang menjalankan berbagai program deradikalisasi ini harus melakukan refleksi Apakah selama ini program tersebut sudah mencapai tujuan untuk mengubah piliran dan tindakan para narapidana terorisme itu (deradikalisasi)? Atap hanya melepaskan mereka dari kekerasan ekstrem (disenguge) dan sama sekali belum bisa menyentuh apalagi mengubah pemikiran mereka?
Sejauh ini, program deradikalisasi masih terkesan sebagai program disengagement, yaitu hanya memisahkan mereka dari tindakan kekerasan ekstrem, tapi belum mengubah pemahaman dan pemikiran radikal mereka. Karena itu, wajar bila kita bertanya: apakah program deradikalisasi selama ini sudah efektif?.
*) MANAGING DIRECTOR
YAYASAN PRASASTI PERDAMAIAN
Sumber : Tempo, 2 Juli 2017 | Hal 44